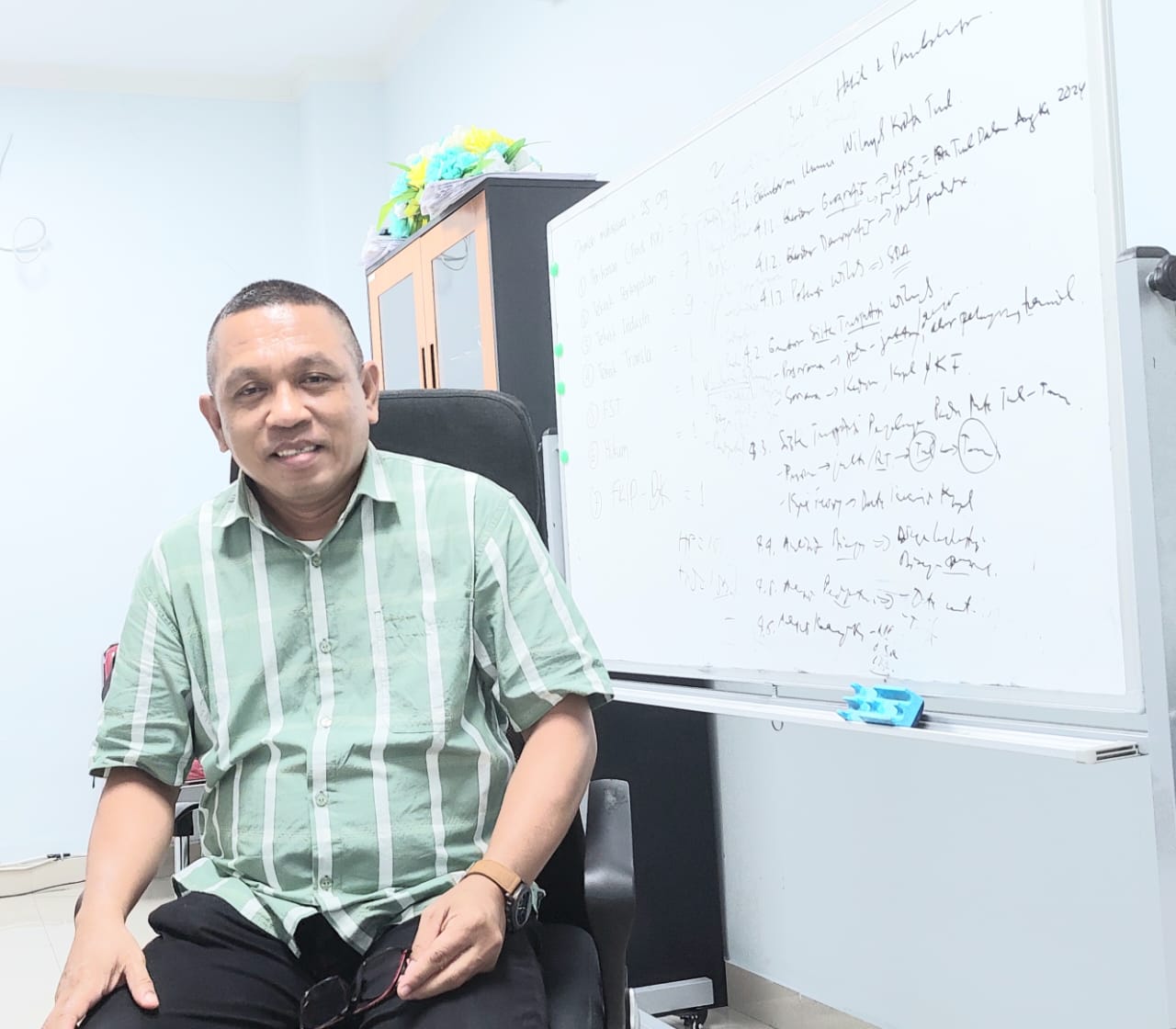Oleh:
Dr. Hanok Mandaku, S.T., M.T.
(Dosen Prodi Teknik Transportasi Laut UNPATTI)
Gagasan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) sebagai pelabuhan utama yang terintegrasi dengan kawasan industri dan logistik regional adalah sebuah langkah strategis. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi gerbang ekspor-impor Maluku, tetapi juga sebagai simpul utama dalam jaringan distribusi antarpulau Kawasan Timur Indonesia. Namun, pertanyaan mendasar yang masih mengemuka dan menimbulkan perdebatan, adalah: di mana lokasi ideal untuk MIP dibangun?
Pertanyaan ini bukan sekadar urusan teknis atau administratif. Lokasi MIP akan menentukan masa depan konektivitas ekonomi Maluku. Karena itu, penentuan lokasi tidak boleh berbasis pertimbangan politis atau sentimen lokalistik, melainkan berdasarkan pada analisis fungsional, geografis, dan ekonomi-logistik yang objektif dan terukur.
Pelabuhan Adalah Fungsi, Bukan Sekadar Titik
Dalam teori Location Theory oleh Alfred Weber dan diterapkan dalam konteks pelabuhan oleh Rodrigue (2020), lokasi pelabuhan ideal adalah titik minimum total biaya logistik antara sumber daya, pasar, dan distribusi. Artinya, pelabuhan harus dibangun di lokasi yang memungkinkan efisiensi maksimum bagi arus barang, baik masuk maupun keluar, dengan memperhatikan kedalaman laut, aksesibilitas hinterland, serta potensi pengembangan jaringan transportasi darat dan laut beserta infrastruktur pendukungnya.
Dengan pendekatan ini, ada beberapa parameter objektif yang seharusnya digunakan dalam menilai kelayakan lokasi MIP, yakni: Pertama, dekat dengan pusat produksi dan konsentrasi permintaan logistik, misalnya kawasan industri, pertanian, perikanan, atau energi. Maksudnya adalah bahwa pelabuhan ideal harus berlokasi sedekat mungkin dengan sumber barang (komoditas) yang akan dikirim, maupun konsumen atau pelaku usaha yang membutuhkan barang tersebut. Hal ini berkaitan langsung dengan prinsip efisiensi logistik. Menurut teori Least Cost Location dalam geografi ekonomi (Weber, 1909) dan Logistics Chain Efficiency dalam transportasi (Rodrigue, 2020), semakin dekat pelabuhan dengan pusat produksi dan distribusi, maka biaya dan waktu pengangkutan dapat ditekan secara signifikan, baik untuk ekspor maupun distribusi dalam negeri.
Kedua, memiliki konektivitas multimoda, yakni terhubung dan bisa dilayani oleh jalan nasional, pelayaran antarpulau, atau bahkan moda udara dalam ekosistem logistik. Maksudnya adalah bahwa lokasi pelabuhan yang ideal harus terhubung dengan berbagai moda transportasi lainnya—baik darat, laut, maupun udara—sehingga dapat mendukung kelancaran dan efisiensi distribusi barang dalam ekosistem logistik secara menyeluruh. Dalam teori Multimodal Transport System (Rodrigue, 2020), efisiensi rantai pasok sangat bergantung pada kemampuan berpindah antar moda transportasi secara lancar. Dengan demikian, konektivitas multimoda memungkinkan MIP tidak berdiri sendiri, tapi menjadi simpul dalam jaringan logistik terpadu yang mendukung ekspor, distribusi antarwilayah, dan pergerakan barang lintas moda.
Ketiga, memiliki kedalaman laut dan perairan yang aman untuk kapal besar, serta potensi pengembangan dermaga skala regional. Maksudnya adalah bahwa lokasi pelabuhan harus berada di perairan yang cukup dalam dan tenang, sehingga dapat melayani kapal-kapal berukuran besar secara langsung tanpa perlu pengerukan besar-besaran atau perlakuan khusus, serta memiliki ruang pengembangan fisik ke depan. Pelabuhan ideal harus berada di perairan yang secara alami memiliki kedalaman laut yang cukup, biasanya minimal 10–12 meter untuk kapal niaga ukuran menengah dan >14 meter untuk kapal kontainer besar atau kapal kargo ekspor-impor. Disamping nautika pelabuhan, aspek pengembangan mengisyaratkan garis pantai yang relatif panjang dan stabil untuk memungkinkan ekspansi dermaga seiring pertumbuhan volume barang. Sehubungan dengan itu, teori Port Planning and Site Selection (UNCTAD, 1991; Rodrigue, 2020) menjadi dasar dan prinsip utama dalam pemilihan lokasi pelabuhan, yakni “minimum marine and civil engineering intervention”. Maknanya, adalah pemilihan lokasi pelabuhan mesti sedemikian rupa agar intervensi konstruksi di laut seminimal mungkin, demi menghemat biaya, menjaga lingkungan, dan menjamin keberlanjutan operasional.
Keempat, tersedia lahan yang cukup luas untuk kawasan penyangga, pergudangan, dry port, dan pengembangan kawasan ekonomi pelabuhan. Maksudnya adalah bahwa lokasi pelabuhan harus memiliki ruang darat yang memadai agar dapat dikembangkan secara bertahap untuk mendukung fungsi-fungsi logistik dan ekonomi yang menyertai kegiatan pelabuhan. Pelabuhan modern bukan hanya tempat kapal sandar dan bongkar muat barang, tetapi juga merupakan pusat distribusi, pemrosesan logistik, dan zona ekonomi yang terintegrasi. Menurut teori Port Regionalization (Notteboom & Rodrigue, 2005), pelabuhan saat ini telah berkembang dari sekadar “gate” menjadi platform logistik regional yang memerlukan integrasi antara pelabuhan dan hinterland (wilayah belakang). Oleh sebab itu, lahan darat yang luas dan dapat dikembangkan adalah syarat utama agar pelabuhan dapat mengikuti proses ini secara bertahap.
Maluku Butuh Pelabuhan Terpadu, Bukan Sekadar Dermaga
Selama ini, pelabuhan-pelabuhan di Maluku bersifat tersebar dan fragmentatif. Di Ambon, pelabuhan Yos Sudarso dan Pelni menjalankan fungsi yang tumpang tindih, sementara pelabuhan-pelabuhan lain di Tiakur, Saumlaki, Dobo, Tual, Namlea, atau Amahai beroperasi dalam kapasitas lokal tanpa integrasi fungsi logistik. Konsep MIP hadir untuk mengonsolidasikan fungsi-fungsi tersebut menjadi satu simpul utama, mirip konsep hub and spoke dalam teori jaringan transportasi (Button, 2010). Namun, jika lokasi MIP ditetapkan di wilayah yang sulit dijangkau, minim hinterland, atau jauh dari arus komoditas, maka potensi integrasi itu justru tidak akan tercapai. Pelabuhan besar akan sepi muatan karena tidak terhubung dengan sistem produksi dan distribusi.
Dalam literatur perencanaan pelabuhan (Rodrigue, 2020; UNCTAD, 1991), pelabuhan modern didefinisikan bukan sebagai terminal laut semata, tetapi sebagai platform logistik dan industrialisasi. Ini disebut juga sebagai port-centric development, yakni pengembangan kawasan ekonomi berbasis pelabuhan. Maka itu, MIP tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, melainkan dirancang sebagai infrastruktur strategis yang menggerakkan ekonomi regional secara menyeluruh. MIP harus menjadi simpul logistik, pusat industri maritim, dan pintu gerbang ekspor-impor, bukan hanya tempat sandar kapal. Tanpa pendekatan integratif ini, investasi besar dalam pelabuhan akan sia-sia, dan Maluku kembali hanya menjadi titik singgah, bukan titik tumbuh.
Penentuan Lokasi Alternatif: Objektif Dalam Menilai
Hingga saat ini, telah mengemuka sejumlah pandangan tentang lokasi MIP yang ideal. Misalnya, ada pandangan bahwa wilayah Tulehu atau Batu Gong (di Pulau Ambon bagian timur) memiliki potensi karena kedalaman laut yang baik dan relatif dekat dengan pusat kota. Namun, ada juga gagasan untuk menempatkan MIP di luar Pulau Ambon —seperti di Waisarisa, Pulau Seram, Namlea, Pulau Buru, dan Tual, Maluku Tenggara— dengan dalih distribusi wilayah pembangunan. Bila merujuk pada keempat parameter diatas, maka masing-masing lokasi tersebut memiliki keunggulan. Misalnya, Pelabuhan Tulehu dan Batu Gong memiliki kelebihan berkenaan dengan parameter kedekatan dengan pusat produksi dan distribusi utama di Pulau Ambon, serta memiliki akses yang sangat baik terhadap moda transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, kondisi perairan di wilayah ini relatif tenang dan aman untuk pelayaran. Sementara itu, Waisarisa di Pulau Seram dan Namlea di Pulau Buru menawarkan keunggulan dari sisi ketersediaan lahan luas dan kedekatan dengan sumber produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Adapun Tual menonjol dalam hal fungsi pelabuhan eksisting dan kedekatannya dengan sentra perikanan, serta memiliki perairan yang stabil dan lahan cukup untuk pengembangan.
Dalam hal ini, pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) bisa digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan multikriteria (Saaty: 2000), sehingga semua parameter dapat terwadahi secara objektif. Konsep AHP bisa didekati dengan mempertimbangkan faktor teknis (kedalaman, gelombang, geoteknik), faktor ekonomi (biaya investasi, potensi muatan, konektivitas), faktor sosial (akses penduduk, dampak sosial), serta faktor lingkungan (potensi abrasi, ekosistem pesisir). Tanpa model seperti ini, keputusan akan rawan dipengaruhi subjektivitas dan kepentingan sesaat.
Kesimpulan: Utamakan Fungsi, Bukan Sentimen
Maluku membutuhkan pelabuhan utama yang efisien, strategis, dan mampu menjawab tantangan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia. MIP seharusnya menjadi tulang punggung sistem logistik nasional di kawasan ini, bukan sekadar proyek infrastruktur yang monumental di atas kertas. Karena itu, penentuan lokasi MIP harus diletakkan pada prinsip dasar perencanaan wilayah dan sistem transportasi, bukan pada persepsi, tekanan politik, atau kompromi birokrasi. Jika kita gagal menempatkan pelabuhan di lokasi yang tepat hari ini, maka dalam beberapa dekade ke depan, kita akan kembali pada pola lama: pelabuhan besar tapi tidak produktif.
Mari kita belajar dari kota-kota pelabuhan besar dunia — dari Singapura, Busan, hingga Rotterdam — bahwa keunggulan pelabuhan tidak ditentukan oleh klaim administratif, tapi oleh logika rantai pasok yang efisien dan terkoneksi.(*)
Lokasi Maluku Integrated Port dan Logika Rantai Pasok