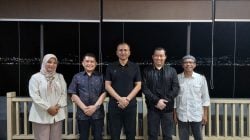Konflik antarkampung seolah belum juga redup dari catatan panjang Maluku. Setiap tahun rentetan peristiwa kekerasan dengan alasan mabuk atau sengketa soal batas tanah selalu saja membawa luka.
Beragam cara dalam penanganan untuk menyudahi konflik kekerasan antarkampung di Maluku itu telah dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan para agent perdamaian dalam bentuk imbauan namun sayang tidak membuat reda.
Dalam suatu diskusi yang digelar Moluccas Democratization Voice (MDV) di Ambon, 1 Maret 2014, pernah menyoal konflik antarkampung ini dan diakui hal itu tak lepas sebagai bagian dari dampak perkembangan demokratisasi dan reformasi, (Rakyat Maluku, 3/4/14).
Salah satu alasan, menurut pembicara DR.Abdul Manaf Tubaka akademisi IAIN Ambon itu, karena terbukanya kran kebebasan sipil dalam mengekspresikan kehendak diikuti perkembangan otonomi daerah dan klaim legitimasi adat yang tidak sejalan oleh penguatan civil society dan menjadi salah satu pangkal konflik komunal masih sering terjadi.
Dalam diskusi yang dipandu Direktur MDV Rizal Sangaji itu mereka mencoba menelaah kasus pertikaian antarkampung Iha-Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan perlunya keseriusan pemerintah menengahi konflik antarkampung. Sebelumnya konflik serupa juga pernah terjadi antara Mamala-Morela, dan Porto-Haria.
Selain DR Manaf Tubaka, juga tampil sebagai narasumber yakni budayawan Maluku M. Noer Tawainella, dan Ketua Umum MASIQA Maluku DR Ruslan Tawari.
Dalam sebuah wawancara saya bersama mantan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum, Kamis, (29/12/22), ia mengakui konflik batas tanah dan antarkampung di Maluku ini merupakan persoalan lama.
Dari hasil kajian di lapangan ditemukan setidaknya ada 52 titik konflik dan menjadi tugas para pemangku kepentingan di Maluku untuk menyelesaikan secara bertahap persoalan batas tanah dan klaim adat ini agar mendapat kepastian hukum.
Saat mengawali tugasnya Januari 2021 itu mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) ini langsung diperhadapkan oleh konflik kekerasan di Pulau Haruku diikuti oleh beberapa peristiwa serupa di tempat lain.
Untuk menghindari konflik komunal terkait persoalan batas tanah dan klaim adat ini penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Kita tentu tidak ingin karena alasan itu kemudian dijadikan sebagai ajang untuk saling menyerang.
Dari catatan mantan wartawan The Jakarta Post M.Aziz Tunny, lebih sebulan terakhir konflik pertama pecah di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, 16 Maret 2025. Akibat konflik itu tercatat dua orang meninggal dunia. Sementara korban luka mencapai 16 orang, sembilan diantaranya anggota polisi.
Konflik kedua terjadi di Hari Raya Idul Fitri, 31 Maret 2025 antara warga Tial dan Tulehu di Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Bentrok ini mengakibatkan satu warga meninggal dunia, dan dua warga mengalami luka serius. Beruntung aparat keamanan cepat memblokade wilayah perbatasan sehingga menggagalkan aksi saling serang antar kampung.
Belum reda kabar duka kembali lagi datang dari Pulau Seram, 3 April 2025. Konflik ketiga ini terjadi antara warga Sawai dan Rumaolat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah rumah dibakar, dan seorang anggota polisi tewas tertembak di kepala.
Dari pengalaman kita selama ini pola-pola kekerasan itu selalu saja diawali oleh sentimen berdasarkan identitas yang diawali dengan orang mabuk, tabrakan, atau perkelehian antarpemuda.
Terlalu beresiko jika karena alasan itu kemudian diikuti oleh sentimen antarwarga berdasarkan identitas kelompok untuk melakukan kekerasan segala.
Karena itu, kepastian hukum menyangkut kekerasan sosial baik alasan mabuk dan tindak kekerasan lainnya perlu ditangani secara serius. Termasuk klaim batas tanah perlu ada penanganan khusus oleh pemerintah agar tidak ada lagi pihak yang merasa tercederai karena menganggap tanahnya dirampas oleh identitas atau komunitas berbeda dengan tujuan tertentu.
Budayawan Maluku M. Noer Tawainella mengakui, konflik yang terjadi saat ini di Maluku tidak lagi melibatkan antar group, tetapi deviasinya mengarah kepada konflik internal atau yang sering disebut konflik komunitas.
Yang menjadi pertanyaan kita mengapa konflik-konflik komunitas itu tidak pernah selesai karena di sana ada arogansi masing-masing kelompok dan menganggap dirinya yang paling dominan.
M.Noer Tawainella menilai, konflik mestinya melahirkan pencerahan dan pencahayaan. Yakni ketika kita belajar dari konflik mestinya membuat kita menjadi lebih cerdas.
Konflik juga merupakan pengalaman untuk kita menimba pelajaran, mendapatkan solusi penyelesaian dengan merujuk kepada akar-akar sejarah. Paling tidak, hal ini bisa menjadi alat penyelesaian konflik di antara mereka yang bertikai.
Kita tentu tak bisa memungkiri bahwa sikap dan perilaku manusia selamanya ditentukan oleh lingkungan dimana ia tumbuh dan besar di situ.
Konflik sosial terjadi selamanya karena dipengaruhi oleh pola pikir, sikap, karakter, dan perilaku seseorang. Hal itu terbentuk melalui proses panjang berdasarkan lingkungan tempat dimana mereka berada.
Kita tahu bahwa konflik itu sendiri adalah sebuah realitas sosial dan merupakan bagian dari respon manusia atas lingkungan sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tak bisa menghindar dari konflik.
Di sini tugas pemerintah dan aparat keamanan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial harus melakukan penyelesaian jika terjadi pertikaian antarwarga. Sayang, implementasi dari UU tersebut seolah belum maksimal sehingga negara dalam hal ini terkesan gagal dalam melindungi dan memberikan rasa aman bagi warganya.
Jika alasan batas tanah dan klaim adat menjadi problem sosial sehingga menyebabkan nyawa dan harta benda menjadi korban — mestinya negara dengan semua perangkatnya sudah harus punya jalan keluar untuk mendeteksi sejak dini setiap ancaman konflik komunal di daerah ini.(*)